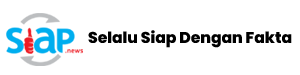Oleh: Suryadi dan Helsi Dinafri
Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL). Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi.
ABUSUS non tollit usum. Ungkapan Latin yang dapat diartikan “Penyalahgunaan tidak boleh menjadi kebiasaan” ini, agaknya pas untuk Hoegeng. Ia bereksistensi memulai dari diri sendiri, kemudian mewujud sebagai sosok yang bersikap “satu kata dengan perbuatan”.
Paham filsafat eksistensialis menyebut “manusia adalah eksistensi”. Manusia tidak hanya ada dan berada tapi “mengada”. Manusia tidak semata-mata tunduk pada kodratnya dan secara pasif menerima keadaan, tetapi ia selalu secara sadar dan aktif menjadikan dirinya sesuatu. Proses perkembangan manusia, sebagian ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan itu ia berkarya (Sarlito W. Sarwono, 2019: 42).
“Mengada”, tentu saja berbeda dengan mengada-ada. Mengada-ada, jelas dibikin-bikin sehingga terbangunlah sandiwara yang secara ekstremnya dapat dikatakan palsu.
Hoegeng jika masih hidup sampai 14 Oktober 2021, genap berusia 100 tahun. Ia wafat 14 Juli 2004 atau 12 hari setelah Hari Bhayangkara ke-54. Waktu itulah “Iman Santoso” baru dicantumkan sehingga tertera lengkap nama “Hoegeng Iman Santoso”, di batu nisan kuburnya 17 tahun silam.
Di bulan Agustus 2021 muncul sebuah publikasi yang pada intinya Hoegeng manusia langka: “Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, di negeri ini tak ditemukan sosok sekaliber Hoegeng (juga Bung Hatta, pen), bersih dan antikorupsi.” Pada grup WhatsApp yang sama, seorang jurnalis menyergah: “Pasti ada! Tidak ‘terexpose’ saja”.
Dalam bingkai optimistik, mungkin jurnalis itu ada benarnya, tapi ada nilai plus yang tak dimiliki banyak orang. Seorang polisi (baca: penegak hukum) Hoegeng setia pada kebenaran dan secara berani berkonfrontasi, meski harus kehilangan jabatan tinggi yang pada banyak kasus membuat si pemegang jabatan tega bermewah-ria di tengah tebaran “musibah kemiskinan” yang ada setiap hari di depan mata.
Adalah sebuah kebenaran realitas ketika kewenangan dan kekuasaan yang menyertai jabatan digunakan secara “cepat saji” untuk kenikmatan pribadi, kerap cuma memberi kenikmatan semusim. Bertolak belakang dengan itu, pada kebenaran realitas pula, Hoegeng melegenda seiring dengan konsitensinya hidup sederhana. Sekali lagi, hidup dengan tidak mengada-ada.
Widodo Budidarmo, Kapolri ke-7, mengaku mengenal Hoegeng seniornya sejak masa perpeloncoan di awal-awal menjadi mahasiswa PTIK Angkatan III (1955). Di matanya, Hoegeng adalah sosok yang manusiawi, mempunyai dedikasi dan komitmen kepada profesi polisi. Ia sangat memerhatikan tingkat kriminalitas dan masalah-masalah sosial yang rawan, seperti sengketa tanah dan buruh.
Hoegeng adalah Kepala Bagian Rerese Kriminal Kepolisian Sumut di akhir 1950-an. Widodo yang menjadi Kepala Kepolisian Sumut setelah Hoegeng berdinas di Mabes Polri, banyak mendengar cerita-cerita tentang seniornya yang disegani oleh banyak kalangan di Sumut. Hoegeng banyak meninggalkan nama baik, lantaran ia tak kenal kompromi terhadap semua kejahatan, utamanya penyelundupan dan perjudian.
Dalam sepak terjangnya, Hoegeng lebih menyukai action di lapangan ketimbang banyak bicara.
Sebagai seorang pemimpin polisi, ia jujur dan penuh dedikasi. Salah satu pesannya, “Mas Widodo, …Jangan sampai polisi bisa dibeli.”
Tentang kehidupan Hoegeng yang sederhana, Widodo mengungkapkan (Santoso dkk.,2009: 192).:
“Pak Hoegeng dan keluarganya sangat sederhana. Kalau makan saja selalu
seadanya. Saat inimenikahkan putra-putrinya sederhana sekali, jauh dibandingkan
dengan pejabat-pejabat lain yang jor-joran menggelar pesta yang besar dan mewah.
….Pak Hoegeng memang pemimpin yang pantas dijadikan panutan generasi penerus.
Widodo yang dipromosikan dari Kepala Kepolisian Sumut menjadi Kepala Kepolisian Metro Jaya semasa Hoegeng Kapolri, melihat seniornya itu peduli dan mencintai Bhayangkara sampai sesudah pensiun sekalipun. Sebagai purnawirawan Polri, Hoegeng masih banyak memberikan perhatian lewat pesan-pesannya yang sangat berharga dan informasi-informasi yang kredibel bagi Kepolisian.
Tentang kecintaan dan kepedulian Hoegeng kepada institusi polisi yang sudah ia masuki mulai zaman Jepang, bukan sesuatu yang omong kosong. Wartawan senior Panda Nababan punya catatan khusus tentang Kapolri karibnya itu. Di tahun 1978 Panda adalah wartawan Sinar Harapan. Dalam suatu kunjungan ke rumah Panda di Gang Tembok Cikini, Jakarta Pusat, Hoegeng sambil menunjukkan surat pribadinya kepada Kapolri Widodo, berkata: “kamu mau saya kasih berita besar?”
Surat pribadi Hoegeng kepada Kapolri Widodo itu berbunyi, “Wid, sekarang ini polisi sudah kaya-raya. Ada yang membeli rumah di Kemang (Jakarta Selatan, pen) dan membuat jalan pribadi beraspal.” Bekal informasi ini diteruskan Panda, hingga terlacak polisi itu adalah Kolonel Srs, Pamen di Jawatan Keuangan Polri.
Setelah investigasi, termasuk melalui seorang Komandan Provost Polri yang ternyata “pengagum berat Hoegeng” tercium lah bau busuk korupsi itu. Jumlahnya mencapai Rp 4,8 miliar, angka yang fantastis untuk masa itu. Kasus ini berujung di pengadilan dengan terdakwa Letjen Pol (kini Komjen). Swj Deputi Keuangan Kapolri, dan tiga bawahannya. Dalam catata lembaran hitam Kepolisian itu, tertulis Swj divonis delapan tahun ditambah denda Rp 7 juta. Tiga bawahannya masing-masing divonis oleh majelis hakim enam tahun penjara (Santoso dkk., 2009: 292 – 294).
Tentang keterbukaan seniornya itu, kata Widodo, dapat dilihat dari sikapnya yang tidak menjauhi wartawan. Selama kepemimpinan Hoegeng sebagai Kapolri sering diadakan interview dan press meeting. Pengakuan terkait keterbukaan Hoegeng, juga dirasakan Panda. Misalnya, Hoegeng sebagai Kapolri membekalinya surat pribadi ketika di tahun 1970-an ia meliput Kasus Perkosaan Bakul Telur di Yogyakarta, tahun 1970-an.
Surat pribadi Hoegeng tersebut ditujukan kepada Komandan Kepolisian Yogya untuk Panda “berjaga-jaga”. Sebab, peristiwa yang dikenal dengan Kasus Sum Kuning tersebut cukup sensitif. Dari empat nama yang disebut-sebut terlibat, di antaranya menyeret-seret dua nama anak petinggi Yogyakarta, Pakualam dan Danrem/ Pahlawan Revolusi, Brigjen Katamso.
*Pembentukan Karakter*
DARI yang terurai di sepanjang perjalanan hidup Hoegeng, baik ketika memegang jabatan tinggi Negara maupun setelah pensiun karena diberhentikan, terbaca jelas siapa sosok Hoegeng. Tanpa pretensi politik apalagi sekadar popularitas, Hoegeng melaju dengan sikap dasarnya: egaliter, terbuka, jujur, bersih, tidak korup yang membuat ia mampu apa adanya hidup dalam kesederhanaan.
“Satunya kata dengan perbuatan” membuat ia tetap hidup dihormati didampingi Mery istri tercinta serta anak-anak yang jauh dari terfasilitasi oleh kekuasaan Hoegeng sebagai pejabat Negara. Toh ia tetap bisa bahagia dan bergembira sambil menjalani hobinya melukis dan bermusik hawaian. Karena bermusik itu pula, ia bersama Mery sempat diundang oleh Yamaha ke Jepang. Terkait itu, sejumlah penyanyi muda Indonesia kala itu, termasuk Broery Marantika, terorbit oleh lomba yang diadakan Yamaha di sana. Mengapa Hoegeng bisa sekokoh itu?
Pendidikan bukan cuma dimulai dari kecil, tapi ketika anak masih dalam kandungan. Dunia pendidikan mengenal tiga lingkungan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan sepanjang pertumbuhan anak hingga remaja menjemput masa dewasa. Pertama, keluarga khususnya kedua Ibu dan Ayah. Kedua, lingkungan masyarakat. Ketiga, Pemerintah atau lingkungan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal.
Sejak dulu hingga kapan pun ketiga lingkungan tersebut, tak bisa bersilepas dari tanggung jawab atas kelangsungan pendidikan anak-anak. Lingkungan, tak cuma dipahami berwujud fisik dengan segala keformalan yang membalutnya, tetapi melekat sampai ke persoalan yang mengakibatkan tak tergalinya potensi kejiwaan anak didik atau bahkan bila sampai terjadi perkembangan yang menyimpang.
Hoegeng lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan, sebuah karesidenan di pesisir utara Jawa. Tepatnya di Kampung Pesatean, kawasan yang dulunya merupakan salah satu perkampungan Arab. Letak Pesatean tak jauh dari Bong Cina, sebuah kompleks pekuburan Cina (Yusra dan Ramadhan, 1993: 15). Ia lahir dari Ibu Oemi Kalsoem asal Pemalang, sedangkan Ayahnya, Sukario Kario Hatmodjo berasal dari Tegal. Sejarawan Prof. Asvi Warman Adam menulis, Hoegeng berasal dari seorang Ayah yang abangan dan Ibunya penganut agama yang taat (Santoso dkk., 2009: 7 dan xv). Mereka muslim.
Ciri egaliter wong Pekalongan, diakui Hoegeng sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang mengkultur dalam dirinya dan teman-temannya, sejak kecil dan terbawa-bawa hingga dewasa. Sejarawan Asvi menulis, “Sikap terbuka dan tidak takut kepada atasan bila benar itulah yang dipegang Hoegeng selama bertugas.” (Santoso dkk., 2009: xvi).
Kultur egalitarian masyarakat kota Pekalongan itulah yang telah diserap oleh Hoegeng. Kelak di kemudian hari sikap-sikap itu pula yang membuat Hoegeng menjadi sosok yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam berhubungan dengan setiap manusia, di mana pun berada, dan siapapun yang ia hadapi.
*Nilai-Nilai*
NILAI-nilai keteladanan dipetik oleh Hoegeng antara lain dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari keluarga Amtenar. Ayahnya ningrat dari lingkungan keraton Mataram, Yogyakarta. Tetapi, status sosial dan keningratan tak membuat ayah dan ibunya itu menjadi manusia yang diskriminatif. Kepada Hoegeng, ayahnya secara khusus meminta untuk selalu memelihara kehormatan dengan basis kejujuran dan bersih.
Nilai-nilai yang sejalan dengan agama menjadi panduan dalam segala situasi. Ia bukan sekadar beragama, tapi begitulah sosok Hoegeng menyerap nilai-nilai agama dan egalitarian (lihat “Masyarakat Egaliter”, Louise Marlow, 1997: 15 – 23) dalam kehidupan sehari-harinya. Dari situ memunculkan tiadanya perbedaan antar sesama manusia kecuali iman dan takwa yang jadi pembeda sebagaimana ajaran agama yang dianut Hoegeng dan mayoritas masyarakat Pekalongan itu sendiri.
Teman-teman ayahnya, antara lain Ating Natadikusumah, Kepala Djawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan, serta Kepala Pengadilan Pekalongan, Soeprapto. Ketiganya adalah “tiga serangkai” yang telah menjadi role model bagi Hoegeng. Sejak kecil Hoegeng bercita-cita menjadi seorang polisi. Ia termotivasi oleh sosok Ating yang kepadanya berpesan (Yusra dan Ramadhan, 1993: 45):
“…kekuasan itu ibarat pedang bermata dua. Kalau tidak pandai
menggunakannya maka bisa mendatangkan bahaya. Ingat,
hanya orang berilmu yang mampu menggunakan kekuasaan yang
ada dalam tangannya untuk menolong orang-orang yang lemah
dan tidak bersalah.”
Pada saat yang sama semasa di Pekalongan, Hoegeng bergaul dan berteman dengan orang-orang dari beragam suku bangsa Nusantara, juga dengan mereka yang berbeda ras dengan bahasa. Jadi, bukan aneh kalau Hoegeng sampai menguasai Bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis.
Lingkungan masyarakat Pekalongan menjadi latar yang banyak memengaruhi Hoegeng. Ia menyebut Pekalongan pada masa itu telah memiliki ciri-ciri modern yang sudah lebih heterogen. Di sini telah berjalan sistem politik pemerintahan, pendidikan, serta fasilitas umum seperti perkantoran, air ledeng, dua rumah penjara, pengadilan negeri, lapangan olahraga, hotel, dan tempat-tempat hiburan. Tersedia pula HIS (SD) dan Mulo (SMP) yang di tempat lain masih langka tersedia.
Dengan itu semua, pada Hoegeng secara psikologi lebih banyak terbangun sikap yang meneladani nilai-nilai dari keluarga yang menjunjung kehormatan dan kemanusiaan. Tak kurang pentingnya adalah keberadaan Pemerintah penjajah (Hindia Belanda dan Jepang). Realitas itu, ia temukan baik di Pekalongan maupun saat melanjutkan pendidikan di AMS Yogya dan kuliah hukum di RHS Batavia.
Seiring dengan kronik perjalanan hidupnya di kota-kota yang berbeda-beda satu sama lain, sadar atau tidak telah membuat Hoegeng mampu memfilter berbagai nilai dari lingkungan tempat ia bertumbuh. Satu hal lagi, yaitu disiplin keras yang pada masa itu mungkin saja dipandang bengis oleh bangsa Indonesia yang terjajah (oleh Belanda dan Jepang), tapi kini justru terasa begitu mahal didapat.
Begitu banyak filter yang dapat memengaruhi perilaku Hoegeng dalam pembentukan keyakinannya tentang yang benar dan salah (nilai-nilai), serta bangunan identitas dan kepribadiannya. Semua berlangsung sejak ia anak-anak sampai remaja sehingga terinternalisasi dalam-dalam, kemudian menjadi identitas saat ia dewasa.
Hoegeng telah tumbuh di atas berbagai pilihan-pilihan nilai, yang mungkin saja secara bijak telah ia seleksi sehingga akhirnya ia memulai dari diri sendiri (baca: kesadaran akan identitas diri). Itu pula, agaknya, yang membuatnya teguh dan kukuh dalam bersikap, ketika menghadapi berbagai situasi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar yang telah tertanam kuat dalam dirinya.
Sepanjang hayat, Hoegeng telah mengkomunikasikan suatu keteladanan, pertama-tama bukan melalui kata-kata, melainkan dengan perilaku. Keteladanan bergulir, termasuk kepada ketiga anaknya.
Sejak lama hingga kini adalah fakta, bahwa korupsi dan tabiat korup sebagai perbuatan jahat telah menimbulkan banyak kemudharatan dan itu amat dimusuhi Hoegeng. Tetapi, nyatanya, korupsi terus membiak dalam kehidupan masyarakat yang “gampang memaklumi dan memaafkan, asalkan kebagian”. Korupsi terjadi seperti bergiliran saja; hari ini siapa, besok siapa lagi, dan yang berikutnya giliran siapa pula.
Di “tiga lingkungan penanggung jawab pendidikan”, mungkin saja ada peran-peran yang sengaja tidak dimainkan oleh para pemerannya, sehingga kemampuan memfilter nilai-nilai dari lingkungan tak lagi berfungsi baik. Kapasitas Negara dalam melahirkan role model pun patut dipertanyakan, sementara seremoni-seremoni antikorupsi terus digelar.
Ketika orang meningkat remaja, lalu menjadi dewasa, besar harapan terbangunnya identitas yang teguh di atas dasar-dasar yang kuat. Sosok serupa ini, akan mampu memilah milah, mana yang cocok dan mana pula yang tidak sesuai untuk menjadi identitas dirinya. Dengan kata lain mengkarakter. Karakter semacam ini akan terbangun lewat pendidikan dalam arti luas, bukan seperti kerap terdengar dalam guyonan: “Untuk disiplin, apakah harus mendatangkan penjajah”.
Komunikasi keteladanan, telah dibawakan oleh Hoegeng dan oleh orang hebat lainnya di negeri ini, yang mungkin saja jumlahnya tidak banyak. Tetapi, adalah kenyataan keteladanan orang-orang hebat itu kerap terkalahkan oleh gerusan nilai-nilai buruk tapi secara instan mengantarkan pada kenikmatan. Mungkin penyebabnya adalah kapasitas pendidikan yang diharapkan bukan sekadar berkutat pada kejaran keterampilan fisik; pendidikan yang tak terfasilitasi secara baik oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Pembentukan sikap pada seseorang, kata psikolog senior (alm) Sarlito Wirawan Sarwono, dapat terjadi melalui empat macam cara: (1) Adobsi, yaitu menerima peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang dan terus-menerus yang lama-lama kelamaan terserap menjadi suatu sikap. (2) Diferensiasi, yaitu kemampuan membedakan suatu objek seiring berkembangnya intelejensi, pengalaman, dan usia. (3) Integrasi, yakni pembentukan sikap secara bertahap karena berbagai pengalaman yang berhubungan degan suatu hal. (4) Trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba dan mengejutkan, meninggalkan kesan mendalam sehingga dapat menyebabkan terbentuknya sikap. (2019:203-205):
Maka, kehadiran role model secara berulang-ulang dan terus menerus dalam kerangka itu, menjadi faktor kuat yang senantiasa penting dihidup-hidupkan, dan harus selalu ada di semua lini kehidupan. **