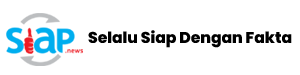1. IMAN SANTOSA HOEGENG
Oleh: Suryadi, Wasekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)/
Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL).
Helsi Dinafri, Praktisi Komunikasi
“Animo magis quam corpore aegri sunt”. “Mereka yang berkuasa
lebih banyak terkena sakit jiwa,” ungkapan Latin mengingatkan.
Seperti melengkapi, ilmuwan Inggris Loc Acton (1833 – 1902) menambahkan, “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely”, “Kekuasaan cenderung korup. Kekuasan absolut,
korupsi absolut”. Namun, tak demikian dengan Jenderal Pol. Hoegeng.


Ia “melawan” (dalam tanda petik) dan melawan kekuasasan, termasuk kepada penguasa yang telah memilihnya
menjadi Kapolri. Bahkan, ia dengan keluguan dan kejujuran
menundukkan kekuasaannya sendiri. Ini bukan kultus individu.
Senyatanya, Hoegeng cuma manusia biasa yang juga dengan ringan
dan konkret spontan mengakui bawahan. Hoegeng menjadi Kapolri (9 Mei 1968 – 2 Oktober 1971) berdasarkan Keppres RJ. No. 131/ABRI/1968. Kapolri ke-5 lulusan PTIK Angkatan I/Parikesit (1952), ini, digantikan oleh Mohammad Hasan, yang lebih junior namun lebih
tua usia dari padanya. “Iman Santoso” baru dicantumkan di batu nisan
kuburnya mengikuti nama Hoegeng ketika ia berpulang dan dimakamkan
17 tahun silam (14 Juli 20024). Keimanan memang bukan untuk difesivalkan.
Nama Hoegeng senantiasa memang pantas berada di panggung
sejarah penegakkan hukum. Keteladanannya tak pernah kering untuk
digali. Layak diteladani baik oleh generasi penerus Polri maupun
yang berada pada kekuasaan, yakni penegak hukum lainnya seperti
KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Juga, mereka yang berada di
pemerintahan, legislatif, dan tak kalah pentingnya oleh masyarakat
umum yang cenderung banyak keliru memahami tentang permakluman
dan permaafan “asalkan kebagian”.
Jika Hoegeng masih ada sampai
14 Oktober 2021, ia genap berusia seabad. Tulisan ini hanya Sebagian
dari perjalanan hidupnya, yang tersaji dalam Sembilan bagian. Sejarah
selalu saja menyisakan hal yang tak terungkap. Tetapi bagaimanapun,
“…inti dari nilai sejarah adalah moral judgement yang disampaikan kepada masyarakat lewat public history,” sejarawan Inggris, Prof. Ludmila
Jane Jordannova mengingatkan (Pranoto, 2010: 7):
MENYEBUT nama Hoegeng, secara umum orang melihatnya sebagai manusia yang apa adanya, sederhana, dan antikorupsi. Oleh karena itu, ia bersih dari dekil-dekil yang dapat menodai setiap jabatan yang ia sandang sampai saat ia berada di titik akhir puncak karirnya, sebagai Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Pangak/Pang-AKRI, sekarang Kapolri) pada 1971. Bahkan, saat sudah menikmati masa-masa pensiun, kepeduliannya terhadap antikorupsi, tak kurang-kurang.
Penilaian yang dilekatkan pada sosoknya itu, tak berlebihan. Itu sama sekali bukan “merk dagang” atau “iklan politik” agar ia laku “dijual”. Jangan-jangan jika ia masih ada dan berada dalam partai politik (Parpol), lantas terjun di gelanggang politik Indonesia di masa kini yang serba pragmatis dan transaksional ini, malah membua peluang partainya “tidak laku” dan berujung “bangkrut”.
Sepanjang memegang berbagai jabatan tinggi, baik di dalam maupun di luar institusi Kepolisian, ia tetap mempertahankan identitasnya sebagai polisi (baca: penegak hukum) yang jujur dan bersih. Ia tak goyah oleh berbagai pemberian yang ia nilai bukan haknya. Tak ada kompromi, samar-samar atau nyata-nyata illegal. Ia menolak tegas apa pun yang patut diduga bakal menumpangi fungsi dan jabatan yang disandangnya.
Misalnya, ketika dari Jawa Timur, ia dimutasi ke Medan menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabagreskrim) Kepolisian Sumatera Utara (Sumut) (1956). Ia memerintahkan cukong-cukong mengeluarkan kembali barang-barang mahal berupa perabotan rumahtangga yang mereka kirim ke rumah dinasnya. Karena tak kunjung dikeluarkan, akhirnya, ia sendiri bersama sejumlah anggota polisi anak buahnya mengeluarkan barang-barang mewah tersebut. Tindakan serupa juga ia lakukan ketika jelang lebaran banyak berdatangan kiriman parcel untuknya dan keluarga.
Perilaku Hoegeng yang demikian itu, sekaligus dimaksudkan mengoreksi keras siapa pun yang membukakan akses ke rumah dinas yang ia inginkan tetap clean sepanjang sebagai pejabat dan pribadi. Tidak main-main!
Ketika menjadi Kapolri, ia dengan kesadaran penuh sebagai pejabat tinggi Negara tak mau menerima dan memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi semacam previllage baginya.
Ia menolak penggunaan mobil dinas oleh keluarga; menolak membuat memo untuk anaknya masuk sekolah. Contoh, ketika anak keduanya, Aditya, masuk AKABRI Udara, Hoegeng sengaja mengulur-ulur waktu. Tiba habis waktu setor keterangan pencantumkan siapa orangtuanya, Aditya pun kehilangan kesempatan.
Tindakan dan sikap Hoegeng yang lahir dari kesadaran itu mengingatkan kepada filsuf Prancis, Rene Descartes (1596 – 1650). Bersemboyan Cogito ergo sum (aku berpikir, maka aku ada), Descartes berpandangan, tugas psikologi adalah menganilisis kesadaran. Ia menggambarkan, kesadaran terdiri dari unsur-unsur struktural yang sangat erat hubungannya dengan proses-proses panca indera.
Banyak yang menentang teori ini. Misalnya, Sigmund Freud, yang justru menganggap kesadaran hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis (Suryabrata, 2003: 6).
Terbayangkan betapa keras dan kuatnya Hoegeng menggali dari kesadarannya sendiri, agar terhindar dari godaan menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan dan kesenangan pribadi. Padahal, Saat itu kontrol publik seperti LSM belum ada. Pengawas internal sudah ada, tapi senantiasa “kompromis” dengan alasan demi “nama baik” institusi dan Pemerintah. Seperti iklan yang sering dianekdotkan “jeruk makan jeruk”. Media sosial (medsos), yang di masa kini menjadi sarana bagi setiap orang yang mau setiap saat bisa seketika mengekspresikan ke publik mulai dari kebencian sampai memfitnah, juga belum ada.
Pada saat itu Hoegeng justru sudah memulai dari diri sendiri sebagai sosok yang terbuka dan bersih. Bukan sebaliknya, menjadi pejabat yang culas memanfaatkan kekuasaan untuk menumpuk-tumpuk harta kekayaan dan memfasilitasi anak-anaknya berbisnis. Risikonya, ya hidup sederhana apa adanya bersama keluarga di tengah kehidupan masyarakat yang kian hedonistik.
Sebagai Kapolri, Hoegeng memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Madura (kini Jalan M. Yamin) No. 8, Menteng, Jakarta Pusat, meski Negara menyediakan rumah jabatan. Bertahun-tahun menghuni rumah sewa yang jauh dari mewah, akhirnya dapat ia membelinya. Tetapi, beberapa waktu setelah pensiun, terpaksa ia jual lagi menyusul uang pensiunnya yang terlalu kecil (Suhartono, 2013: 133) dibandingkan besarnya biaya-biaya di kawasan elit Menteng.
Hoegeng menjual rumah tersebut pada 1998, namun ia masih diizinkan oleh si pembeli menempatinya sampai tahun 2000, sambil menunggu rumah barunya selesai dibangun di Kota Depok, Jabar –dekat selatan Jakarta. Sebelumnya, segera setelah pensiun, ia mengembalikan semua barang-barang inventaris Kapolri kepada Markas Besar Kepolisian (Mabak), seperti mobil dinas, walkie talkie, peralatan radio, dan lainnya. Ia sendiri tidak punya mobil, namun mengaku tak merasa ada hambatan kemana-mana menumpang Mercedes. Maksudnya, bus Mercedes yang melayani angkutan umum di DKI Jakarta.
Padahal, pada masa itu bahkan hingga kini, sudah menjadi rahasia umum jika seorang pejabat pensiun, cenderung berusaha memiliki barang-barang inventaris dinas, termasuk mobil dan rumah jabatan. Hal ini terfasilitasi oleh aturan yang memang memungkinkan untuk hal itu. Contoh, pensiunan Presiden dan Wapres, yang memang diatur oleh Undang-Undang, berhak mendapat rumah jabatan. Meski sudah memiliki rumah pribadi yang cukup representatif, mereka tetap mau menerima fasilitas dari Negara itu. Ada lagi pejabat yang justru tanpa malu-malu membawa keluar barang-barang inventaris dari rumah dinas, kemudian baru mengembalikannya setelah media heboh.
Berbeda dengan Hoegeng. Suatu ketika, tak lama setelah pensiun, Kapolri penggantinya, Mohammad Hasan tergerak sengaja mendatangi dan “mendamprat” Hoegeng, “Kamu kok gila-gilaan, kok semua barang kamu kembalikan?” Kepada juniornya yang lebih tua itu, Hoegeng hanya berkata, “Habis, kan memang bukan milik saya.” Pada pertemuan nan akrab itu, Jenderal polisi Hasan yang berasal dari Muaradua, Sumsel itu, sempat menawari Hoegeng mobil. ”Bagaimana kalau saya pinjami?“ Cogito er sum, semboyan Descartes.
Orang Samin
DALAM sekapur-sirih “Hogeng Polisi dan Menteri Teladan” (HPMT), Prof. Adrianus Meliala, membandingkan dengan situasi sekarang saat penggunaan mobil dinas dan lain sebagainya, sudah menjadi sesuatu yang diregulasi dan diawasi. Orang ramai-ramai melanggarnya dengan berbagai alasan. Maka, mestinya ada sesuatu yang berbeda pada diri Hoegeng, bahkan untuk ukuran waktu itu. Catatan penulis untuk ukuran masa kini, anak-anak remaja sering beromentar untuk hal serupa itu: “Enggak gitu-gitu juga kali.”
Saking bedanya, kriminolog UI Adrianus Meliala menggambarkan, jika Hoegeng masih aktif hari-hari ini, maka kemungkinan besar ia akan dijuluki ‘orang Samin’. Julukan itu mengacu pada komunitas masyarakat di Pulau Jawa yang terbiasa berpikir dan bertindak amat lugu dan logis. Jika aturannya begitu, ya begitu. Jika sesuatu dinyatakan terlarang, ya sudah jangan dilakukan.
“Di benak orang Samin tidak ada fleksibilitas atau pun tenggang rasa. Apa kata aturan, ya ikuti saja.… Bisa dibayangkan betapa kerepotan yang timbul jika orang seperti Hoegeng menjadi Kapolri hari-hari ini” (Suhartono. 2013: xix- xx). Apa yang bakal terjadi? Jika benar bahwa hari-hari ini korupsi dan modus lain yang “haram” sudah menjadi sebuah mainstream demi menopang gaya hidup, maka Hoegeng adalah sosok sebaliknya.
Masyarakat Samin hidup mewarisi budaya tani. Mereka bermukim mengelompok di Dusun Tambak –sekitar 40 km dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mereka menjalani hidup dengan lugu, apa adanya. Lebih kurang seperti digambarkan Adrianus tadi. Tetapi, setidaknya menurut penulis, Hoegeng adalah orang biasa yang mampu menundukkan diri sendiri sehingga ia menjadi “luar biasa” di tengah tinggi dan menggiurkannya trend godaan “nikmatnya” memetik hasil dari penyalahgunaan kekuasan.
Hoegeng hidup dan menjadi polisi sejak masa-masa pahit hingga gampangnya menikmati kekuasaan dengan melanggar; dari zaman Jepang hingga lima – enam tahun pertama Orde Baru (Orba) berkuasa. Ia bertahan hidup seperti itu, karena secara mendasar melihat dirinya sendiri sebagai orang biasa. Demikian pula ketika melihat orang lain. Di matanya, tak ada strata sosial yang membuatnya harus meninggikan atau sebaliknya rendahkan seseorang dari yang lain atau dari dirinya.
Tentang sikapnya, ia dalam “Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan” (HPIK), mengungkapkan:
“Saya sendiri, agaknya sudah sampai pada semacam sikap dasar demikian.
Jika saya berhadapan dengan seseorang, maka saya tidak mengukur seseorang dari kedudukannya atau status sosialnya. Tidak juga dari perbedaan posisi, paham,
dan pilihan politik, atau perbedaan ras dan golongan. Jika saya berhadapan dengan seseorang maka saya menghadapinya sebagai manusia. Paling tidak sikap demikian yang saya dambakan dalam kehidupan ini.” (Yusra dan Ramadhan, 1993: 18). **